SUMELEH, SEMELEH: SIGNIFIKANSI ESTETIKA KERONCONG GAYA SOLO
Abstract
Surakarta (Solo), yang dilegitimasikan sebagai kota keroncong, memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan pelestarian musik keroncong di Indonesia. Dengan berbagai hegemoni yang dilakukan, di tengah maraknya kreasi dan inovasi di era serba modern, masyarakat keroncong Solo masih mempertahankan sajian musik keroncong yang menjunjung tinggi nilai estetika keroncong gaya Solo. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan signifikansi estetika keroncong gaya Solo bagi para pelaku maupun penikmat musik keroncong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu terkait puncak estetika keroncong gaya Solo dan signifikansinya. Untuk mencapai puncak estetika keroncong gaya Solo, terdapat berbagai unsur yang membangun dan aturan-aturan tertentu. Signifikansi utama dari sajian musik keroncong gaya Solo yang telah mencapai puncak estetikanya yakni disebut dengan istilah sumeleh/semeleh. Istilah ini diidentifikasi dalam beberapa sub-bahasan, di antaranya sumeleh dalam kebahasaan dan makna, sumeleh sebagai emosi yang mempengaruhi perilaku, serta sumeleh sebagai pengalaman estetis (estesis) yang berkaitan dengan subjek, objek, dan nilai estetis. Sumeleh digambarkan oleh masyarakat keroncong Solo sebagai suatu keadaan/suasana hati yang tenteram dan tenang. Manfaat penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pelaku maupun penikmat musik keroncong.
Kata kunci : Sumeleh, Signifikansi Estetika Keroncong, Keroncong Gaya Solo
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Abdi, A. S., Hotimah, A. N., Rahmawati, D. D., Alfi, L. B. M., & Devi, M. S. (2020). Syair-Syair Patah Hati: Kajian Semiotika Lagu-Lagu Didi Kempot Dalam Era Disrupsi. Unej E-Proceeding, 272-287.
Asriyani, N., & Rachman, A. (2019). Enkulturasi Musik Keroncong Oleh Ok Gema Kencana Melalui Konser Tahunan Di Banyumas. Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik, 1(2), 74-86.
Fikri, M. T., & Mistortoify, Z. (2019). Prospel: Kemunculannya Pada Musik Keroncong. Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni, 12(2), 51-61.
Garibaldi, P., & Hapsara, P. (2019). Analisis Teknik Permainan Biola Pada Voorspell Keroncong Senyuman Candra. Selonding, 15(2), 83-89.
Kistanto, N. H. (2017). Kesenian & Mata Pencaharian-Upaya Seniman Tradisional & Populer Dalam Pemenuhan Nafkah. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 7(1), 43-86.
Kodir, K., Margiyati, M., Ningrum, T. F., & Amalia, D. (2020). Pengaruh Kombinasi Terapi Relaksasi Progresif & Musik Keroncong Terhadap Insomnia Pada Lansia Di Posyandu Setya Manunggal Iii Kabupaten Semarang: The Effect Of Combination Of Progressive Relaxation Therapy & Keroncong Music On Insomnia In The Elderly At Posyandu Setya Manunggal Iii, Semarang Regency. Jurnal Keperawatan Sisthana, 5(2), 46-51.
Marta, K. S. (2021). Motivasi Dan Apresiasi Siswa Terhadap Musik Keroncong Di Sman 2 Jombang. Jurnal Pendidikan Sendratasik, 10(2), 151-171.
Mulyadi, R. M., & Indira, D. (2019). Dualisme Pelestarian Dan Pengembangan Musik Keroncong Pada Tahun 1970-An. Metahumaniora: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya, 9(1), 76–86.
Maulana, S., Tjahjodiningrat, H., & Sukanta, K. (2022). Pengaruh Aransemen Musik Keroncong Terhadap Minat Para Pendengar Grup Musik Keroncong Tujuh Putri Pada Musik Keroncong The Effect Of Keroncong Music Arrangements On The Interest Of The Keroncong Music For Keroncong Tujuh Putri Listeners. Cinematology: Journal Anthology Of Film And Television Studies, 2(2), 99-115.
Prabowo, B. R. (2019). Kualitas Personal Dalam Mencapai Estetika 'Ngroncongi'. Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni, 14(1),1–9.
Rachman, A., Pangesty, S. D., Haryono, S., Sunarto, S., & Lestari, W. (2022). Improvisasi Melodi Instrumen Flute Dalam Musik Keroncong. JPKS (Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni), 7(2).
Rachman, A., & Utomo, U. (2017). “Sing Penting Keroncong” Sebuah Inovasi Pertunjukkan Musik Keroncong Di Semarang. JPKS (Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni), 3(1).
Ramadhani, F. A., & Rachman, A. (2019). Resitensi Musik Keroncong Di Era Disrupsi: Studi Kasus Pada OK Gita Puspita Di Kabupaten Tegal. Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik, 1(1), 41-51.
Shaleha, R. R. A. (2019). Do Re Mi: Psikologi, Musik, Dan Budaya. Buletin Psikologi, 27(1), 43–51.
Sokhiba, S. F., & Rachman, A. (2021). Proses Belajar Menyanyi Keroncong Melalui Tradisi Lisan Di Semarang. JPKS (Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni), 6(1).
Sukmayadi, Y., Supiarza, H., & Andini, M. (2022). The Learning Stages Of Ngroncongi/Undul Usuk: Achieving The Original Solo Keroncong Singing Style. Malaysian Journal Of Music, 11(1), 84-108.
Supiarza, H., & Sarbeni, I. (2021). Teaching And Learning Music In Digital Era: Creating Keroncong Music For Gen Z Students Through Interpreting Poetry. Harmonia: Journal Of Arts Research And Education, 21(1), 123-139.
Supiarza, H., Setiawan, D., & Sobarna, C. (2019). Pola Permainan Alat Musik Keroncong Dan Tenor Di Orkes Keroncong Irama Jakarta. Resital: Jurnal Seni Pertunjukan, 20(2), 108-120.
Zandra, R. A., & Rustopo, R. (2020). Politik Dan Situasi Sosial Dalam Sejarah Keroncong Di Indonesia. Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni, 15(1), 6-11.
DOI: https://doi.org/10.17509/swara.v3i2.32991
Refbacks
- There are currently no refbacks.
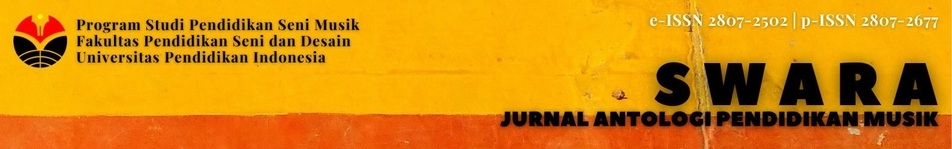
1.png)
1.png)
